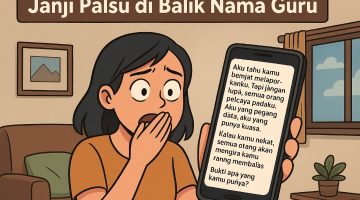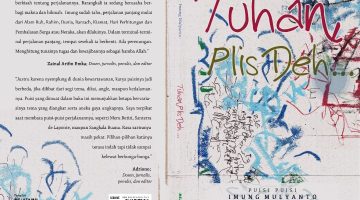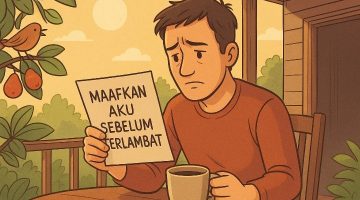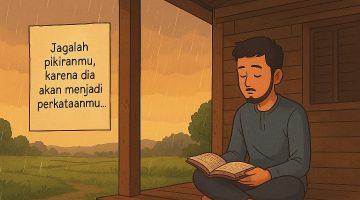Jakarta, Majalahjakarta.com – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Peduli Nusantara Tunggal (DPP PPNT) yang fokus pada advokasi kebijakan publik menegaskan, secara hukum Eigendom Verponding merupakan hak milik mutlak atas tanah yang berakar dari sistem hukum perdata barat. Namun, status hukum tersebut sudah tidak berlaku lagi dalam sistem pertanahan Indonesia modern. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), negara melakukan unifikasi pertanahan, yakni upaya penyatuan dan penyederhanaan hukum agraria nasional agar selaras dengan prinsip keadilan sosial dan kepastian hukum. Melalui proses ini, seluruh hak-hak lama, termasuk bekas Eigendom Verponding, dikonversi menjadi hak-hak baru yang diakui oleh hukum nasional.
Eigendom Verponding dalam Hukum
Asal-usul dan Konsep Dasar
Istilah Eigendom Verponding berakar dari sistem hukum kolonial Belanda. Dalam bahasa Belanda, eigendom berarti hak milik mutlak, sedangkan verponding merujuk pada harta tetap atau tanah yang dikenai pajak. Dalam praktik kolonial, hak ini memberikan kekuasaan penuh kepada pemegangnya untuk menggunakan, menikmati, dan memindahtangankan tanah secara absolut-sebuah konsep yang jelas berkarakter individualistik dan kapitalistik, khas hukum perdata barat.
Status Hukum Saat Ini
Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, sistem hukum pertanahan Indonesia menghapus dualisme hukum kolonial dan adat. Akibatnya, hak Eigendom Verponding tidak lagi diakui sebagai dasar kepemilikan tanah yang sah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Segala bentuk alat bukti tertulis tanah hak barat juga dinyatakan tidak berlaku. Tanah-tanah bekas Eigendom Verponding kemudian berstatus sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sampai dilakukan penyesuaian melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Konversi Hak
Sebagai bentuk transisi hukum, pemegang hak Eigendom Verponding wajib melakukan konversi haknya menjadi salah satu bentuk hak atas tanah yang diatur dalam UUPA, seperti hak milik, hak guna bangunan (HGB), atau hak pakai.
Langkah ini menjadi strategi hukum untuk meneguhkan kedaulatan agraria nasional, sekaligus memastikan bahwa seluruh tanah di wilayah Indonesia tunduk pada sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Unifikasi Pertanahan dalam Hukum Publik
Tujuan dan Signifikansi
Konsep unifikasi pertanahan lahir sebagai bagian dari agenda besar pembaruan hukum agraria nasional. Tujuannya adalah menyatukan dan menyederhanakan sistem hukum pertanahan yang sebelumnya terpecah antara hukum perdata barat dan hukum adat.
Melalui unifikasi ini, pemerintah berupaya membangun satu sistem hukum pertanahan yang adil, transparan, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan asal-usul hukum hak atas tanah.
Perangkat Hukum dan Pelaksanaan
Dalam kerangka hukum publik, unifikasi pertanahan diwujudkan melalui konversi hak-hak lama-termasuk bekas Eigendom Verponding-menjadi hak-hak baru yang sesuai dengan ketentuan UUPA dan peraturan pelaksananya.
Kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung makna politik hukum, yaitu membebaskan sistem pertanahan Indonesia dari warisan kolonialisme menuju sistem yang berdaulat dan berkeadilan sosial.
Kepastian Hukum dan Dampaknya
Dengan diberlakukannya sistem unifikasi pertanahan dan mekanisme konversi hak, diharapkan terwujud kepastian hukum bagi para pemegang hak atas tanah.
Langkah ini memungkinkan setiap warga negara memiliki bukti kepemilikan yang jelas, sah, dan terintegrasi dalam sistem hukum pertanahan nasional yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Lebih jauh, unifikasi ini menjadi fondasi penting bagi tata kelola agraria modern, yang menempatkan tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga instrumen pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kewajiban Konversi sebagai Syarat Kepastian Hukum
Dalam sistem hukum pertanahan nasional, konversi hak merupakan langkah krusial bagi pemegang bekas Eigendom Verponding agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang sah.
Melalui mekanisme konversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, setiap pemegang hak lama diwajibkan untuk menyesuaikan status kepemilikannya menjadi salah satu bentuk hak baru, seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Pakai.
Kewajiban ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari penegakan prinsip kepastian hukum dalam tata kelola agraria nasional. Dengan melakukan konversi, pemegang hak mendapatkan jaminan legalitas kepemilikan yang diakui oleh negara dan tercatat secara resmi dalam sistem pendaftaran tanah nasional.
Langkah ini juga menegaskan peralihan dari sistem hukum kolonial menuju sistem hukum agraria yang berdaulat dan berpihak pada rakyat Indonesia.
Konsekuensi bagi yang Tidak Melakukan Konversi
Sebaliknya, bagi pemegang hak yang tidak melakukan konversi hingga batas waktu yang ditentukan, terdapat implikasi hukum yang tegas.
Status kepemilikan tanah tersebut tidak lagi diakui secara hukum dan tanahnya dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Artinya, negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, mengelola, dan menetapkan peruntukan atas tanah tersebut sesuai dengan kepentingan umum dan kebijakan pembangunan nasional.
Situasi ini menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Tanah yang tidak dikonversi berpotensi kehilangan nilai legalitasnya, sehingga tidak dapat dijadikan objek transaksi, jaminan, atau warisan yang sah.
Lebih dari itu, ketidakpatuhan terhadap kewajiban konversi dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi generasi berikutnya, serta membuka ruang sengketa agraria yang seharusnya dapat dihindari.
Status Hukum Tanah Bekas Eigendom Verponding: Antara Penguasaan Negara dan Kepastian Hukum Rakyat
Dari Warisan Kolonial Menuju Tata Kelola Agraria Nasional
Dalam sejarah hukum agraria Indonesia, Eigendom Verponding merupakan simbol dari sistem pertanahan kolonial yang bercorak individualistik dan kapitalistik. Eigendom berarti hak milik mutlak, sedangkan Verponding merujuk pada pajak atas benda tetap seperti tanah atau bangunan. Dalam praktik kolonial Belanda, kepemilikan atas tanah dengan status eigendom memberikan kekuasaan penuh kepada individu, dengan pajak tahunan (verponding) sebagai kewajiban administratif.
Namun, seiring lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, sistem tersebut resmi tidak lagi diakui sebagai dasar kepemilikan tanah di Indonesia. UUPA menjadi tonggak unifikasi hukum agraria, menghapus dualisme antara hukum barat dan hukum adat, sekaligus mempertegas prinsip kedaulatan negara atas tanah sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Status Hukum Tanah yang Tidak Dikoversi
Masalah muncul ketika tanah-tanah bekas Eigendom Verponding tidak dilakukan konversi oleh pemegangnya sesuai ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda, ditegaskan bahwa seluruh benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda yang tidak termasuk dalam ketentuan nasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958, serta pemiliknya telah meninggalkan wilayah Indonesia, dikuasai oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri (Muda) Agraria.
Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki hak penguasaan langsung terhadap tanah-tanah yang ditinggalkan atau tidak dikonversi, bukan semata-mata untuk diambil alih secara paksa, tetapi dalam kerangka pengelolaan dan pengaturan agar tanah tersebut dapat digunakan bagi kepentingan yang lebih luas.
Makna Penguasaan Negara: Antara Administrasi dan Kepentingan Publik
Sebagaimana dijelaskan Prof. Arie Sukanti Hutagalung dalam Jurnal Law Review (2010:146), penguasaan negara terhadap tanah merupakan amanat konstitusional yang bermakna aktif: negara tidak hanya memiliki kewenangan administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan pengelolaan tanah mendukung kesejahteraan rakyat.
Hal ini juga sejalan dengan pandangan Arthur Noija, advokat kebijakan publik yang konsen dalam isu pertanahan, yang menegaskan bahwa penguasaan negara bukan berarti pengambilalihan secara paksa sebagaimana nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Penguasaan di sini lebih dimaknai sebagai wewenang pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, dan memberikan keputusan tentang siapa yang berhak mengelola atau memanfaatkan tanah tersebut.
Dengan demikian, penguasaan negara harus dibedakan secara tegas dari pemilikan negara. Negara bertindak sebagai pengatur dan penjaga keseimbangan kepentingan publik, bukan sebagai pemilik absolut yang dapat bertindak sewenang-wenang atas tanah rakyat.
Lemahnya Sosialisasi dan Keadilan Konversi
Di lapangan, kebijakan konversi sering kali tidak diikuti oleh sosialisasi yang memadai kepada masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang dulunya menjadi pusat administrasi kolonial. Banyak pemegang hak lama yang tidak memahami prosedur konversi, atau terkendala administrasi dan biaya. Akibatnya, sebagian tanah bekas Eigendom Verponding jatuh ke dalam status “abu-abu”-tidak jelas siapa pemegang hak sahnya, dan pada akhirnya dikuasai oleh negara tanpa mekanisme kompensasi yang transparan.
Kondisi ini memunculkan kritik bahwa negara seringkali lebih menonjolkan aspek penguasaan daripada perlindungan terhadap hak-hak warga, padahal semangat UUPA adalah mewujudkan keadilan sosial dalam pemanfaatan tanah. Tanpa kebijakan afirmatif yang berpihak pada masyarakat, penguasaan negara bisa berubah menjadi bentuk baru dari ketimpangan struktural dalam sistem agraria nasional.
Eigendom, Verponding, dan Spirit Unifikasi Hukum
Dalam konteks hukum perdata barat, Pasal 570 KUHPer menyebut eigendom sebagai hak untuk menikmati suatu kebendaan secara penuh, selama tidak bertentangan dengan hukum atau merugikan hak orang lain. Sedangkan verponding diartikan sebagai pajak atas benda tetap-termasuk tanah dan bangunan-yang dibuktikan dengan surat eigendom atau sertifikat kepemilikan lain.
Istilah Eigendom Verponding pada dasarnya menunjukkan tanah hak eigendom yang dikenai pajak verponding. Namun, dalam perkembangan sosial-hukum Indonesia, istilah ini mengalami penyederhanaan makna di masyarakat menjadi sekadar “tanah eigendom”. Padahal, keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, terutama pasca pemberlakuan UUPA.
Dari Eigendom Verponding ke UUPA: Transformasi Hukum Tanah Menuju Kepastian dan Keadilan Agraria Nasional
Eigendom Verponding: Hak Kolonial yang Tak Lagi Relevan
Dalam praktik hukum agraria modern, Eigendom Verponding tidak lagi dikenal sebagai alas hak yang sah atas tanah di wilayah Indonesia. Sistem ini merupakan produk hukum kolonial yang menempatkan tanah sebagai objek ekonomi murni, bukan sebagai sumber kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, tanah-tanah bekas Eigendom Verponding tidak dapat lagi didaftarkan haknya tanpa melalui mekanisme konversi sesuai ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.
Secara historis, Eigendom adalah hak milik mutlak berdasarkan hukum perdata barat, sementara Verponding merupakan jenis pajak atas benda tetap seperti tanah dan bangunan. Dalam sistem kolonial, hak ini hanya dimiliki oleh kalangan tertentu, khususnya warga Eropa dan perusahaan-perusahaan besar Belanda.
Namun, setelah Indonesia merdeka, sistem semacam itu bertentangan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Mengapa Eigendom Verponding Tidak Lagi Diakui
Ada beberapa alasan mendasar mengapa hak Eigendom Verponding tidak diakui lagi sebagai salah satu hak atas tanah dan perlu dikonversi ke dalam sistem hukum nasional:
1. Politik Pertanahan Kolonial Bertentangan dengan Cita-cita Nasional
Pasal 51 Indische Staatsregeling (IS) dan Pasal 62 Regerings Reglement (RR) ayat (5) pada masa Hindia Belanda mengatur bahwa pemberian tanah kepada pengusaha besar harus dilindungi.
Ketentuan ini jelas berbanding terbalik dengan filosofi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan tanah sebagai sarana pemerataan kesejahteraan rakyat, bukan alat eksploitasi oleh kelompok modal.
Maka, sistem hukum kolonial yang eksklusif tidak dapat terus dipertahankan dalam tatanan hukum agraria nasional yang berorientasi sosial.
2. Hukum Adat sebagai Jiwa UUPA
UUPA menjadikan hukum adat sebagai dasar utama penyusunan sistem agraria nasional.
Dalam konsideran menimbang huruf (a) UUPA, ditegaskan bahwa struktur ekonomi masyarakat Indonesia pada dasarnya masih bersifat agraris, sehingga pengaturan tanah harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan gotong royong, bukan kepemilikan individualistik sebagaimana hak eigendom.
Kepastian Hukum dan Konversi Hak
Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri, yang baru terwujud ketika hukum telah ditetapkan dan dijalankan dengan adil. Dalam konteks agraria, kepastian hukum berarti kejelasan status dan perlindungan atas hak atas tanah di bawah payung hukum nasional.
Karena itu, ketika UUPA Nomor 5 Tahun 1960 disahkan, ia tidak hanya mengatur prinsip dasar pertanahan, tetapi juga menetapkan mekanisme konversi hak bagi tanah-tanah bekas hak barat, termasuk Eigendom Verponding.
Bagian kedua dari ketentuan konversi dalam UUPA secara tegas menyatakan bahwa pemegang hak lama wajib mengubah status haknya menjadi hak-hak baru seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Pakai.
Tujuan konversi ini bukan semata administratif, tetapi merupakan proses rekonstruksi hukum pertanahan untuk memberikan kepastian hukum yang diakui dan dilindungi oleh sistem agraria nasional.
Sengketa Tanah Bekas Eigendom Verponding: Refleksi dari Lapangan
Isu konversi tanah bekas Eigendom Verponding tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga banyak menimbulkan sengketa hukum di lapangan.
Sebagai contoh, dalam kasus tanah di Kabupaten Tegal (Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Slw), penggugat mengajukan klaim kepemilikan berdasarkan bukti bekas hak Eigendom Verponding. Namun, dalam pertimbangan hukum, pengadilan menegaskan bahwa pengakuan atas bukti tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan konversi dalam UUPA.
Hal ini sejalan dengan Pasal I UUPA, yang menegaskan bahwa “hak eigendom dapat dilakukan konversi menjadi hak milik”.
Artinya, bukti eigendom lama tetap memiliki nilai historis dan administratif, tetapi baru sah secara hukum jika dikonversi menjadi hak yang diatur dalam sistem hukum nasional.
Selanjutnya, Pasal 22 UUPA memperkuat ketentuan ini dengan menegaskan bahwa salah satu cara terjadinya hak milik adalah berdasarkan ketentuan undang-undang.
Dengan demikian, konversi bukan hanya keharusan hukum, tetapi juga jalan menuju kepastian hukum dan legitimasi kepemilikan yang sah.
Ketika Regulasi Tidak Seimbang dengan Realitas
Meski UUPA telah membuka jalan menuju keadilan agraria, tantangan implementasi masih nyata.
Banyak masyarakat-terutama ahli waris pemegang hak lama-tidak memahami mekanisme konversi atau kesulitan mengurus administrasi akibat minimnya sosialisasi dan birokrasi yang rumit.
Akibatnya, tidak sedikit tanah bekas Eigendom Verponding yang berstatus quo, tidak memiliki kepastian hukum, bahkan rawan diklaim oleh pihak lain atau dikuasai negara tanpa proses yang transparan.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir secara adil dalam pelaksanaan konversi hak.
Padahal, semangat UUPA adalah “hukum agraria untuk rakyat, bukan rakyat untuk hukum agraria.”
Oleh karena itu, kebijakan pertanahan seharusnya tidak berhenti pada regulasi, tetapi harus diwujudkan melalui pendampingan, edukasi hukum, dan pelayanan agraria yang pro-rakyat.
Eigendom Verponding Nomor 822: Refleksi atas Konversi Hak dan Asas Nasionalitas dalam Hukum Agraria Indonesia
Salah satu bab penting dalam sejarah hukum agraria Indonesia adalah proses konversi hak-hak barat, termasuk eigendom verponding, menuju sistem hukum nasional yang berlandaskan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Kasus yang melibatkan Eigendom Verponding Nomor 822 menjadi contoh konkret bagaimana dinamika hukum kolonial dan kebijakan nasional bertemu dalam satu garis tegas: penegasan kedaulatan atas tanah dan penguatan asas nasionalitas.
Konversi sebagai Instrumen Unifikasi Hukum
Ketentuan hukum menunjukkan bahwa hak eigendom verponding dapat dikonversi menjadi hak guna bangunan (HGB) atau hak pakai, bergantung pada status kewarganegaraan pemegang hak. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa pemegang hak yang tidak mendatangi kantor pertanahan atau tidak dapat membuktikan kewarganegaraan tunggal Indonesia, haknya akan berubah menjadi HGB.
Konversi bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan mekanisme unifikasi hukum pertanahan yang meneguhkan sistem agraria nasional berdasarkan asas kebangsaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 UUPA.
Asas Nasionalitas dan Penegasan Kewarganegaraan
UUPA secara tegas menempatkan tanah sebagai unsur kedaulatan. Hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hubungan hukum penuh dengan tanah, air, dan ruang angkasa. Oleh sebab itu, pemegang hak eigendom verponding yang tidak dapat membuktikan kewarganegaraan tunggal Indonesia wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan konversi.
Dalam konteks Eigendom Verponding Nomor 822 atas nama Tjoa Tjeng Sioe alias Tjwa Tjang Sioe, langkah konversi ini merupakan pengakuan terhadap hak lama yang perlu disesuaikan dengan hukum agraria nasional, bukan penghapusan sewenang-wenang. Namun demikian, jika tidak dilakukan dalam jangka waktu 20 tahun, hak tersebut secara otomatis berakhir dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Permendagri Nomor 3 Tahun 1979.
Kelemahan Administrasi dan Kepastian Hukum
Meski norma hukum telah jelas, dalam praktiknya muncul sejumlah persoalan. Salah satunya ialah lemahnya sosialisasi dan penegakan administratif terkait kewajiban konversi hak. Banyak masyarakat, terutama ahli waris pemegang hak lama, tidak memahami mekanisme hukum yang berlaku, sehingga haknya berakhir tanpa perlindungan.
Kelemahan ini memperlihatkan bahwa negara sering kali hadir sebagai “penguasa” ketimbang “pelindung hak warga”. Padahal, semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan penguasaan negara atas tanah bukan untuk mengambil alih, melainkan untuk menyejahterakan rakyat.
Antara Sejarah dan Keadilan Sosial
Kasus tanah bekas eigendom verponding seperti Nomor 822 memberi pelajaran penting bahwa transisi hukum dari kolonial ke nasional tidak semestinya hanya diukur dari aspek legal formal, melainkan juga aspek keadilan sosial dan sejarah penguasaan tanah. Negara seharusnya tidak berhenti pada tindakan administratif, tetapi juga perlu membuka ruang rekognisi dan mediasi hukum bagi masyarakat yang secara historis memiliki keterikatan atas tanah tersebut.
Kepastian Hukum Tanah Bekas Eigendom Verponding No. 822: Antara Perlindungan Individu dan Kedaulatan Negara
Isu kepastian hukum atas tanah bekas eigendom verponding hingga kini masih menjadi bahan diskursus yang menarik dan relevan, terutama dalam konteks unifikasi hukum agraria nasional. Kasus Eigendom Verponding Nomor 822 menjadi gambaran konkret bagaimana hukum kolonial berinteraksi dengan hukum nasional pasca-UUPA, dan bagaimana prinsip keadilan serta kepastian hukum diuji dalam praktik.
Makna Ganda Kepastian Hukum dalam Konversi Hak
Dalam konteks agraria nasional, kepastian hukum memiliki dua makna penting.
Pertama, melindungi kepentingan individu agar setiap orang mengetahui batas antara hak dan larangan. Hal ini tertuang dalam Pasal I ayat (1) hingga ayat (5) Ketentuan Konversi UUPA, yang menegaskan bahwa sejak diundangkannya UUPA, semua hak atas tanah harus disesuaikan dengan sistem hak nasional yang berlaku.
Kedua, kepastian hukum berfungsi melindungi warga dari potensi kesewenang-wenangan pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan Umum Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, bahwa semua hak atas tanah asal konversi hak barat berakhir paling lambat pada 24 September 1980, dan sejak saat itu tanah-tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara.
Untuk menata akibat hukum dari ketentuan tersebut, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979, yang menjadi tonggak kebijakan nasional dalam pengelolaan tanah bekas hak barat.
Ketika Pengakuan Sejarah Bertemu Hukum Positif
Kepastian hukum dalam praktik tidak selalu berjalan mulus. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Unr, penggugat tercatat sebagai pemegang hak atas tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Kesongo, sementara tergugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik keluarganya berdasarkan hak lama – eigendom verponding nomor 452 – yang diturunkan dari seorang arsitek Belanda bernama Van der Weigen.
Namun, dalil pengakuan tersebut menjadi lemah karena hak eigendom verponding tidak lagi diakui sebagai dasar kepemilikan pasca-berlakunya UUPA. Dicabutnya Buku II KUH Perdata yang mengatur hak keperdataan atas benda menandai berakhirnya legitimasi hukum bagi hak-hak kolonial tersebut. Dengan demikian, setiap pemegang hak lama wajib melakukan konversi sesuai dengan ketentuan UUPA untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sah.
Konversi dan Tenggat Waktu Hukum
Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 secara tegas mengatur bahwa apabila pemegang hak tidak datang ke Kantor Kepala Pertanahan dalam jangka waktu enam bulan sebagaimana diatur Pasal 2, maka hak eigendom tersebut secara otomatis dikonversi menjadi hak guna bangunan (HGB) dengan jangka waktu 20 tahun.
Berakhirnya masa berlaku hak tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 serta Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979, yang menjadi dasar hukum bahwa tanah yang tidak dikonversi akan berstatus tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
Ketegangan antara Kepastian dan Keadilan
Kritik utama terhadap implementasi kebijakan ini terletak pada ketimpangan informasi dan administratif. Banyak masyarakat, terutama ahli waris pemegang hak lama, tidak mengetahui kewajiban konversi yang diatur secara limitatif. Akibatnya, mereka kehilangan haknya tanpa proses yang adil secara sosial maupun historis.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa dalam praktik, kepastian hukum cenderung berpihak pada negara sebagai pemegang otoritas, sementara aspek perlindungan terhadap individu sering kali terabaikan. Padahal, substansi UUPA tidak sekadar menata hak atas tanah, tetapi juga mengandung nilai keadilan sosial dan kemanusiaan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Menemukan Keadilan dalam Transisi Hukum
Perjalanan panjang dari eigendom verponding menuju sistem agraria nasional adalah cermin dari upaya negara membangun kedaulatan hukum di atas warisan kolonialisme. Namun, proses tersebut semestinya tidak menghapus jejak sejarah dan hak-hak yang masih bisa diakui secara sah melalui mekanisme hukum yang terbuka dan adil.
Kepastian hukum bukan hanya tentang kepastian tertulis, tetapi juga kepastian yang memberi rasa keadilan dan kepastian sosial. Di sinilah tantangan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum: bagaimana menyeimbangkan antara kedaulatan negara atas tanah dan hak individual warga negara dalam kerangka hukum agraria nasional yang berkeadilan.
Kepastian Hukum Tanah Bekas Hak Barat: Negara, Rakyat, dan UUPA dalam Persimpangan Keadilan
Tanggal 24 September 1980 menjadi batas historis dalam perjalanan hukum agraria nasional. Sejak tanggal itu, hak-hak atas tanah asal hak barat – termasuk eigendom verponding – resmi berakhir masa berlakunya dan berubah status menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ketentuan ini tidak hanya menjadi tonggak administratif, melainkan juga simbol transisi dari sistem kepemilikan kolonial menuju tatanan agraria nasional yang berpijak pada kedaulatan rakyat.
Namun, di balik ketentuan hukum tersebut, tersimpan pertanyaan besar: apakah kepastian hukum yang diusung benar-benar menghadirkan keadilan bagi rakyat, atau justru mempertegas dominasi negara dalam menentukan nasib tanah dan ruang hidup masyarakat?
Kepastian Hukum dan Fondasi Ideologisnya
Dalam konteks hukum agraria, kepastian hukum tidak hanya berarti tertib administrasi, tetapi juga harus berpijak pada landasan ideologis dan konstitusional, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menjadi wujud nyata penerapan asas tersebut.
Berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 5 jo. Pasal 20 UUD 1945, UUPA lahir sebagai manifestasi politik hukum agraria yang berkeadilan sosial, bukan sekadar regulasi teknis kepemilikan tanah.
Sebagai undang-undang pokok, UUPA menjadi pijakan utama bagi seluruh peraturan pelaksana di bidang pertanahan, termasuk Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979, yang mengatur secara rinci mengenai berakhirnya masa berlaku hak-hak atas tanah asal hak barat dan penguasaan kembali oleh negara.
Dengan demikian, kepastian hukum dalam agraria bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan hukum bekerja selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kedaulatan rakyat atas tanah.
Kasus Slawi: Negara sebagai Pemegang Hak Tertinggi
Konteks ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Slw, yang menolak gugatan terkait sengketa tanah bekas eigendom verponding dengan amar putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa negara berhak penuh atas tanah yang disengketakan, karena hak lama telah berakhir dan tidak dikonversi sesuai ketentuan UUPA.
Berdasarkan asas hak menguasai negara, negara memiliki kewenangan untuk:
1. Menentukan status hukum tanah pasca berakhirnya hak barat,
2. Menetapkan peruntukan dan pemanfaatan tanah, serta
3. Memberikan hak baru kepada pihak yang memenuhi syarat hukum dan kewarganegaraan.
Menariknya, bagi pemegang hak lama atau ahli waris bekas eigendom verponding, hukum tetap membuka peluang untuk mengajukan permohonan hak baru atas tanah yang bersangkutan. Langkah ini mencerminkan bahwa negara tidak sepenuhnya menutup ruang bagi masyarakat yang masih memiliki iktikad baik untuk menyesuaikan status haknya secara hukum.
Ketegangan antara Keadilan Substantif dan Kepastian Formal
Meskipun secara normatif negara memiliki dasar hukum yang kuat, kebijakan penguasaan kembali tanah bekas hak barat menyisakan ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif.
Di satu sisi, UUPA menegaskan prinsip nasionalitas dan kedaulatan negara atas tanah. Namun, di sisi lain, banyak pemegang hak lama atau keturunannya yang tidak mendapat sosialisasi memadai mengenai kewajiban konversi dan tenggat waktu hukum yang sangat terbatas.
Akibatnya, kepastian hukum yang mestinya melindungi rakyat justru berubah menjadi instrumen yang berpotensi merugikan, terutama bagi masyarakat yang tidak memahami kompleksitas hukum agraria.
Kritik ini penting untuk ditegaskan karena substansi keadilan agraria tidak boleh berhenti pada legalitas administratif, melainkan harus mampu menyentuh dimensi sosial, historis, dan kemanusiaan dari kepemilikan tanah itu sendiri.
Membangun Kepastian yang Berkeadilan
Peraturan seperti Keppres Nomor 32 Tahun 1979 dan Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 pada dasarnya dibuat untuk menjaga tertib hukum dan memperkuat peran negara dalam pengelolaan sumber daya tanah. Namun, pelaksanaannya menuntut kearifan dalam penegakan hukum.
Negara, sebagai pemegang hak penguasaan tertinggi, tidak semestinya hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga fasilitator dan pelindung kepentingan masyarakat.
Artinya, kepastian hukum yang sejati harus mengandung dimensi keadilan sosial, di mana hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sarana rekonsiliasi antara hak sejarah dan kepentingan publik.
Dalam konteks ini, tanah bukan sekadar benda ekonomi, melainkan ruang hidup dan identitas bangsa. Maka, dalam setiap kebijakan agraria, negara dituntut tidak hanya “menguasai”, tetapi juga menyejahterakan dan memanusiakan.
Arthur Noija SH