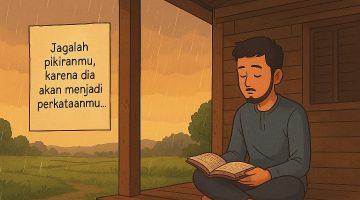Jakarta, Majalahjakarta.com – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Peduli Nusantara Tunggal (PPNT) Jakarta, yang konsisten bergerak dalam advokasi kebijakan publik, menyoroti pentingnya mekanisme praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Praperadilan pada dasarnya hadir untuk memberi perlindungan hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, terutama terkait penetapan status tersangka.
Lahir dari semangat reformasi hukum, lembaga praperadilan dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip due process of law: memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, akuntabel, dan tidak meninggalkan asas kemanusiaan. Pasal 77–83 KUHAP menegaskan kewenangan praperadilan untuk menguji keabsahan tindakan aparat, mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga penetapan status tersangka.
Momentum penting hadir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka dapat diuji melalui praperadilan apabila tindakan itu tidak didukung minimal dua alat bukti permulaan yang cukup, atau dilakukan tanpa prosedur pemeriksaan yang layak. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam memperluas jangkauan perlindungan praperadilan terhadap warga negara.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, dalam praktiknya, efektivitas praperadilan sebagai checks and balances masih menimbulkan perdebatan serius. Di satu sisi, ia dianggap sebagai forum strategis yang memberi ruang keadilan bagi individu yang ditetapkan tersangka tanpa dasar hukum yang kuat. Di sisi lain, tidak sedikit yang menilai lembaga ini justru membuka peluang manipulasi hukum.
Sebagaimana dikritisi oleh Asikin (2023), “praperadilan memang memberi akses terhadap keadilan, tetapi juga membuka celah bagi tersangka untuk menghindari proses hukum melalui dalih formalitas penyidikan yang cacat prosedural.” Pernyataan ini memperlihatkan dilema klasik: antara melindungi hak asasi atau justru melanggengkan impunitas.
Praperadilan: Antara Finalitas Putusan dan Risiko Lolosnya Tersangka
Efektivitas praperadilan dalam membatalkan penetapan tersangka sejatinya sangat ditentukan oleh pemahaman hakim terhadap hukum acara pidana dan prinsip due process of law. Salah satu titik krusial ada pada penafsiran mengenai “dua alat bukti permulaan yang cukup”. Sayangnya, KUHAP tidak pernah memberikan definisi yang jelas mengenai standar maupun bentuk alat bukti permulaan tersebut. Akibatnya, tafsir atas Pasal 1 angka 14 dan Pasal 184 KUHAP menjadi fondasi utama bagi hakim dalam mengevaluasi sah atau tidaknya tindakan penyidik.
Di sinilah problem laten muncul. Seperti diingatkan oleh Supomo (2022), “peran subjektivitas hakim sangat tinggi dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, dan inilah yang menjadikan praperadilan rentan terhadap inkonsistensi putusan antar pengadilan.” Artinya, pada titik tertentu, kualitas perlindungan hukum bagi tersangka amat bergantung pada kualitas nalar dan integritas hakim, bukan semata-mata pada norma hukum yang tertulis.
Namun problem praperadilan tidak berhenti di sana. Tantangan struktural lain yang kerap dipersoalkan adalah finalitas putusan praperadilan. Pasal 83 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa “putusan praperadilan tidak dapat diajukan banding atau kasasi.” Konsekuensinya, jika hakim mengabulkan permohonan praperadilan dan membatalkan penetapan tersangka, maka perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan oleh penyidik, meskipun ada bukti kuat untuk menjerat tersangka.
Kondisi ini menimbulkan paradoks. Harahap (2023) secara kritis menilai bahwa “finalitas putusan praperadilan bisa menjadi paradoks terhadap tujuan penegakan hukum, karena membuka ruang bagi tersangka untuk lolos dari jerat hukum melalui pertimbangan formal semata.” Dengan kata lain, mekanisme yang semula dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia justru bisa dipelintir menjadi tameng bagi pelaku kejahatan.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah waktu pemeriksaan praperadilan yang sangat terbatas. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) KUHAP, praperadilan harus diputus dalam waktu paling lama tujuh hari sejak sidang pertama. Waktu singkat ini seringkali memaksa hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan bukti tertulis dan argumen yuridis, tanpa sempat menggali fakta hukum secara mendalam. Akibatnya, putusan praperadilan cenderung lebih menekankan aspek formil ketimbang substansi materil perkara.
Praperadilan: Mekanisme Singkat yang Menjadi Penjaga Prinsip Keadilan
Menurut Ramadhan (2024), “sifat singkat proses praperadilan menyebabkan pengujian terhadap penetapan tersangka menjadi tidak optimal, karena tidak memberikan cukup ruang untuk mendalami konteks penyidikan secara menyeluruh.” Pandangan ini mengingatkan kita bahwa keterbatasan waktu pemeriksaan bukan sekadar soal teknis prosedural, tetapi juga menyentuh aspek keadilan substantif: apakah praperadilan benar-benar mampu menjadi benteng terakhir hak asasi manusia?
Meskipun penuh keterbatasan, praperadilan tetap dipandang vital dalam sistem hukum Indonesia. Ia adalah mekanisme legal yang dirancang untuk menjamin prinsip perlindungan hukum dan keadilan prosedural. Hal ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), di mana setiap orang tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku kejahatan sebelum terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Oleh karena itu, penetapan seseorang sebagai tersangka tidak bisa dilakukan secara serampangan. Ia harus dilandasi oleh alat bukti yang cukup, sah, dan diperoleh tanpa melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Dalam kerangka ini, praperadilan hadir bukan untuk mengadili materi perkara, melainkan untuk menguji keabsahan prosedur hukum.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 mempertegas hal tersebut. MK menegaskan bahwa “praperadilan merupakan bentuk pengujian konstitusional terhadap prosedur dan legalitas penetapan tersangka, bukan terhadap materi perkaranya.” Dengan kata lain, praperadilan menjadi pagar agar proses hukum tidak berubah menjadi instrumen kekuasaan yang represif.
Namun, di titik inilah dilema muncul. Proses yang singkat membuat hakim kerap terjebak pada formalitas, sementara finalitas putusan praperadilan menutup ruang koreksi jika hakim keliru dalam menilai bukti permulaan. Celah ini dapat melahirkan inkonsistensi putusan antar pengadilan, bahkan membuka ruang manipulasi hukum.
Praperadilan: Penjaga Rule of Law atau Celah Manipulasi Keadilan?
Lembaga praperadilan menempati posisi penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dari potensi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Dalam konteks penetapan tersangka yang cacat prosedur, praperadilan berfungsi sebagai forum korektif untuk menguji legalitas langkah penyidik yang dianggap melampaui batas kewenangannya.
Secara historis, lembaga ini lahir dari semangat menjaga supremasi hukum (rule of law) dan menegakkan keadilan prosedural (procedural justice) dalam proses peradilan pidana. Dengan kata lain, praperadilan bukan sekadar formalitas yuridis, melainkan mekanisme pengawasan agar proses penegakan hukum tidak keluar dari rel konstitusional.
Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP secara tegas mengatur fungsi praperadilan sebagai bentuk judicial control terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan. Ruang lingkupnya mencakup penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penyitaan, penggeledahan, hingga penetapan status tersangka. Artinya, sejak awal penyidikan, warga negara memiliki saluran hukum untuk melawan tindakan aparat yang dianggap tidak sah.
Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa didukung dua alat bukti permulaan yang cukup, sebagaimana disyaratkan KUHAP, praperadilan hadir sebagai forum untuk menguji keabsahan tindakan tersebut. Inilah titik di mana peran hakim praperadilan menjadi sangat menentukan: apakah hukum dijalankan untuk menegakkan keadilan, atau sekadar menjadi stempel formal prosedur.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 21/PUU-XII/2014 bahkan memperluas objek praperadilan, mencakup pengujian terhadap penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Putusan ini menegaskan bahwa hak konstitusional seseorang dapat dirampas sejak ia ditetapkan sebagai tersangka, sehingga pengawasan hakim diperlukan sejak tahap paling awal. Terobosan ini sekaligus mempertegas posisi praperadilan sebagai benteng pertama bagi hak-hak individu.
Namun, di tengah idealitas tersebut, muncul ironi: praperadilan sering kali dipandang ambigu-di satu sisi menjadi pengawas atas potensi penyalahgunaan wewenang, tetapi di sisi lain berpotensi disalahgunakan sebagai alat manipulasi hukum oleh pihak-pihak tertentu. Di sinilah letak kritik publik: apakah praperadilan benar-benar bekerja untuk melindungi kepentingan rakyat, atau justru menjadi celah hukum bagi mereka yang memiliki akses dan kekuatan?
Keberadaan lembaga praperadilan jelas semakin relevan di tengah maraknya kasus penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Akan tetapi, tanpa penguatan integritas hakim dan reformasi regulasi, praperadilan berisiko besar terjebak dalam paradoks: hadir atas nama keadilan, tetapi rawan diperalat untuk kepentingan di luar keadilan itu sendiri.
Praperadilan dan Problematika Penetapan Tersangka: Belajar dari Kasus Budi Gunawan
Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang penetapan tersangka dilakukan secara serampangan—hanya mengandalkan keterangan saksi tanpa dukungan alat bukti lain, atau bahkan tanpa pemeriksaan yang memadai terhadap calon tersangka. Praktik semacam ini jelas melanggar asas due process of law yang menjadi jantung dari hukum acara pidana modern.
Kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi salah satu contoh paling menonjol yang membuka mata publik tentang kelemahan sistem penetapan tersangka di Indonesia. Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, hakim praperadilan menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap Budi Gunawan tidak sah. Pertimbangannya sederhana tetapi fundamental: tindakan tersebut tidak didasarkan pada prosedur yang sesuai hukum acara pidana.
Dalam putusannya, hakim menekankan dua hal penting. Pertama, penetapan tersangka harus dilandasi dua alat bukti yang sah, sebagaimana diamanatkan KUHAP. Kedua, penetapan harus didahului dengan pemeriksaan terhadap calon tersangka agar tidak terjadi pelanggaran hak konstitusional. Mengabaikan dua syarat ini berarti mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan prosedural.
Kasus ini sekaligus menjadi kritik tajam terhadap praktik penyidikan di Indonesia. Bagaimana mungkin seseorang bisa dibebani status hukum yang berat tanpa bukti permulaan yang cukup dan tanpa kesempatan membela diri dalam pemeriksaan awal? Bukankah hal tersebut justru membuka ruang kriminalisasi atas nama hukum?
Efektivitas Praperadilan: Antara Norma dan Praktik
Efektivitas praperadilan sebagai instrumen perlindungan hukum dapat dianalisis dari dua sisi utama: aspek normatif dan praktik yudisial.
Secara normatif, KUHAP memang tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Namun, melalui interpretasi progresif Mahkamah Konstitusi-terutama Putusan No. 21/PUU-XII/2014-serta praktik peradilan, celah normatif tersebut berhasil ditutup. Dengan demikian, dari segi norma, telah tersedia ruang yang memadai bagi tersangka untuk menggugat tindakan aparat yang dianggap sewenang-wenang.
Namun, realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Secara praktik, praperadilan masih menghadapi tantangan serius. Salah satu yang paling menonjol adalah inkonsistensi putusan antar pengadilan dan ketertutupan aparat penegak hukum dalam membuka dokumen penyidikan. Akibatnya, pembuktian di forum praperadilan sering kali berjalan timpang. Tidak jarang, praperadilan berubah menjadi sekadar panggung formalitas ketika bukti-bukti vital justru tidak dapat diakses oleh pemohon-padahal merekalah pihak yang paling membutuhkan informasi itu untuk melawan penetapan tersangka.
Durasi singkat proses praperadilan yang dibatasi maksimal tujuh hari sebagaimana diatur KUHAP juga menambah persoalan. Waktu yang terbatas membuat hakim cenderung mengambil keputusan hanya berdasarkan argumen formil, tanpa sempat menggali fakta hukum secara komprehensif. Situasi ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa pihak termohon-yakni aparat penegak hukum-memiliki keunggulan akses terhadap seluruh alat bukti, tetapi kerap enggan membukanya secara transparan. Ketidaksetaraan ini melemahkan prinsip equality of arms, yang sejatinya menjadi syarat utama bagi proses hukum yang adil.
Meski demikian, praperadilan bukan tanpa harapan. Dalam beberapa kasus, lembaga ini membuktikan dirinya sebagai benteng terakhir perlindungan hukum. Misalnya, Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel dalam perkara Irjen Pol. Djoko Susilo, maupun kasus penetapan tersangka secara prematur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus-kasus tersebut, hakim praperadilan berani mengambil sikap progresif: membatalkan penetapan tersangka yang tidak sah sekaligus memulihkan hak-hak konstitusional individu.
Pengalaman ini sejalan dengan praktik internasional. Dalam banyak negara, fungsi judicial review terhadap tindakan eksekutif dalam proses penegakan hukum dipandang sebagai pilar fundamental negara hukum (Barendt, 2010). Artinya, tanpa mekanisme pengawasan yudisial yang efektif, kekuasaan penegakan hukum berisiko melahirkan penyalahgunaan wewenang.
Praperadilan: Antara Harapan dan Realitas Perlindungan Hukum
Di Indonesia, prinsip perlindungan hukum melalui forum praperadilan memang telah memperoleh pengakuan, meski penguatan kelembagaan dan budaya hukum masih menjadi pekerjaan rumah besar. Menariknya, efektivitas praperadilan kerap ditentukan oleh keberanian hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan substantif, bukan sekadar berpegang pada teks undang-undang.
Menurut Asshiddiqie (2021), “hakim praperadilan bukan hanya mulut undang-undang, melainkan penjaga keadilan pada tahap paling awal proses peradilan pidana.” Pernyataan ini menegaskan betapa pentingnya independensi dan integritas hakim. Hakim yang berani mengoreksi tindakan penyidik pada dasarnya sedang menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara.
Sayangnya, realitas di lapangan sering menunjukkan sebaliknya. Kehati-hatian berlebihan dari hakim justru membuat praperadilan kehilangan taringnya sebagai instrumen kontrol. Padahal, tanpa keberanian itu, forum praperadilan berisiko hanya menjadi seremoni formal tanpa daya korektif.
Selain itu, literasi hukum masyarakat yang rendah turut memperburuk keadaan. Banyak tersangka yang penetapannya cacat prosedur tidak memahami hak-haknya untuk menggugat melalui praperadilan. Keterbatasan akses terhadap bantuan hukum pun memperbesar jurang ketidakadilan. Pada akhirnya, praperadilan lebih banyak dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki sumber daya, sementara kelompok rentan justru semakin termarjinalkan.
Padahal, prinsip-prinsip perlindungan HAM sebagaimana termaktub dalam Pasal 50 KUHP, UUD 1945, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas praduga tak bersalah dan perlindungan hukum sejak awal proses pidana. Di sinilah peran lembaga bantuan hukum menjadi krusial, bukan sekadar akses hukum gratis, melainkan sebagai benteng pemerataan keadilan.
Untuk memperkuat praperadilan sebagai mekanisme kontrol kekuasaan, sejumlah langkah reformasi hukum perlu dipertimbangkan:
1. Revisi KUHAP agar perluasan objek praperadilan yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi memperoleh legitimasi eksplisit dalam undang-undang.
2. Perpanjangan durasi persidangan praperadilan agar proses pembuktian tidak terjebak pada keterbatasan waktu 7 hari yang kerap merugikan pemohon.
3. Kewajiban keterbukaan dokumen penyidikan bagi aparat penegak hukum, sebagai bagian dari asas transparansi dan prinsip fair trial.
4. Pelatihan khusus bagi hakim praperadilan, agar lebih sensitif terhadap isu due process dan HAM, sekaligus berani mengambil putusan progresif ketika hak warga negara terancam.
Tanpa reformasi tersebut, praperadilan hanya akan menjadi forum simbolik, jauh dari cita-cita sebagai penjaga hak konstitusional warga negara. Namun dengan penguatan norma, praktik, dan budaya hukum, praperadilan justru bisa menjelma sebagai salah satu fondasi penting tegaknya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.
Praperadilan: Investasi Demokrasi atau Sekadar Formalitas?
Dalam studi yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR, 2023), ditemukan bahwa “hakim praperadilan yang terlatih dalam pendekatan hak asasi manusia lebih berani mengambil sikap independen terhadap aparat penegak hukum, dan ini meningkatkan efektivitas forum tersebut sebagai pelindung hak-hak tersangka.” Temuan ini membuka mata kita bahwa kualitas praperadilan tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, melainkan juga oleh cara pandang hakim terhadap nilai-nilai keadilan substantif.
Ke depan, efektivitas lembaga praperadilan jelas tidak bisa dilepaskan dari komitmen sistemik terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Praperadilan bukan sekadar prosedur teknis dalam hukum acara pidana, melainkan bagian dari mekanisme check and balances dalam sistem demokrasi. Dalam bahasa sederhana, praperadilan adalah pagar yang membatasi agar kewenangan aparat penegak hukum tidak berubah menjadi alat kesewenang-wenangan.
Namun, realitasnya tidak sesederhana itu. Meski praperadilan memiliki potensi besar sebagai benteng keadilan, dalam praktiknya forum ini sering terjebak pada problem klasik:
1. Kompleksitas sistem hukum yang membuat praperadilan tidak selalu berjalan sesuai harapan.
2. Inkonsistensi putusan antar pengadilan yang melemahkan kepastian hukum.
3. Minimnya literasi hukum masyarakat yang menyebabkan banyak orang tidak menyadari haknya untuk menggugat penetapan tersangka yang cacat prosedur.
Di titik inilah kritik menjadi relevan. Tanpa keberanian hakim, tanpa transparansi aparat, dan tanpa kesadaran masyarakat akan hak-haknya, praperadilan hanya akan berfungsi sebagai ritual hukum, bukan instrumen keadilan.
Maka, menjadikan praperadilan sebagai forum yang kuat, independen, dan inklusif bukan sekadar wacana ideal, melainkan investasi politik hukum jangka panjang bagi masa depan negara hukum di Indonesia. Praperadilan yang efektif akan memberi pesan tegas: bahwa hukum berdiri di atas kekuasaan, bukan sebaliknya.
Praperadilan, Antara Harapan dan Resistensi Penegak Hukum
Dalam praktiknya, praperadilan sering kali menghadapi resistensi dari institusi penegak hukum. Tidak jarang, putusan hakim yang membatalkan penetapan tersangka dianggap sebagai “gangguan” terhadap kewenangan penyidik, alih-alih dihormati sebagai mekanisme kontrol yudisial. Fenomena ini memperlihatkan bahwa prinsip checks and balances antara eksekutif dan yudikatif dalam penegakan hukum pidana belum sepenuhnya berjalan optimal.
Kondisi tersebut kian rumit karena adanya budaya impunitas yang masih mengakar. Aparat yang melakukan pelanggaran prosedural jarang mendapatkan sanksi tegas. Akibatnya, muncul insentif negatif untuk mengulangi tindakan sewenang-wenang, karena tidak ada konsekuensi nyata yang dihadapi.
Padahal, dalam kerangka negara hukum, lembaga praperadilan seharusnya tidak hanya bersifat reaktif-menunggu permohonan diajukan-tetapi juga ditopang oleh sistem akuntabilitas internal yang memastikan setiap tindakan aparat tunduk pada hukum. Dengan begitu, praperadilan berfungsi bukan sekadar “pemadam kebakaran”, melainkan bagian dari mekanisme pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan.
Lebih jauh, penguatan kelembagaan praperadilan membutuhkan dukungan politik hukum yang jelas. Revisi KUHAP mutlak diperlukan agar kewenangan praperadilan tidak hanya bertumpu pada putusan-putusan progresif Mahkamah Konstitusi, tetapi juga memiliki dasar eksplisit dalam undang-undang. Selain itu, dibutuhkan standar operasional prosedur (SOP) penyidikan yang baku dan transparan, sehingga setiap langkah aparat dapat diaudit dan diuji secara objektif.
Namun, hukum tidak hanya urusan lembaga negara. Efektivitas praperadilan juga sangat bergantung pada keberdayaan masyarakat sipil. Organisasi bantuan hukum, media, dan lembaga pengawasan eksternal memiliki peran strategis untuk memastikan proses hukum diawasi publik. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin sempit ruang bagi tindakan kesewenang-wenangan aparat.
Di sisi lain, literasi hukum masyarakat harus ditingkatkan. Banyak orang masih belum memahami bahwa mereka memiliki hak menggugat penetapan tersangka yang cacat prosedur. Padahal, semakin luas kesadaran hukum, semakin kuat pula posisi praperadilan sebagai instrumen perlindungan.
Tidak kalah penting, sistem pendidikan hukum harus mengambil bagian dalam reformasi ini. Kurikulum hukum perlu mencetak generasi baru praktisi dan akademisi yang tidak sekadar menguasai teks undang-undang, tetapi juga memahami nilai-nilai due process of law dan hak asasi manusia. Dengan begitu, kualitas praktik hukum di masa depan akan lebih berpihak pada keadilan substantif, termasuk dalam forum praperadilan yang adil, transparan, dan berimbang.
Praperadilan: Dari Perlindungan Individual Menuju Perbaikan Sistemik
Penguatan lembaga praperadilan sejatinya tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi tersangka secara individual, tetapi juga membawa dampak sistemik terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia. Ketika setiap proses hukum dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur dan menghormati hak asasi manusia, maka kepercayaan publik terhadap institusi hukum akan tumbuh. Dalam jangka panjang, kepercayaan ini menjadi modal sosial penting bagi terciptanya sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Di era digital, penguatan praperadilan harus pula diiringi dengan transformasi teknologi hukum. Sistem pendaftaran daring, akses digital terhadap berkas perkara, hingga publikasi putusan yang terbuka bagi publik bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga akuntabilitas. Lebih jauh, pemanfaatan teknologi analitik dapat membantu mendeteksi pola-pola pelanggaran prosedural yang berulang serta memberikan rekomendasi perbaikan sistemik yang berbasis data. Dengan begitu, praperadilan dapat berfungsi sebagai barometer kesehatan penegakan hukum, bukan sekadar forum formalitas.
Namun, teknologi hanyalah alat. Kualitas hakim praperadilan tetap menjadi kunci. Di sinilah pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan peradilan. Hakim yang menangani perkara praperadilan membutuhkan pelatihan berkelanjutan, pembekalan dalam perspektif hak asasi manusia, serta pengawasan etik yang ketat. Penempatan hakim dengan integritas dan independensi tinggi akan memastikan putusan tidak dipengaruhi tekanan eksternal, baik dari aparat penegak hukum maupun kekuatan politik.
Praperadilan: Pilar Awal Keadilan dalam Negara Hukum
Praperadilan merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang dirancang untuk melindungi hak asasi manusia, terutama dalam menghadapi praktik penetapan tersangka yang tidak melalui prosedur hukum yang sah. Keberadaan forum ini menjadi penyeimbang, agar kewenangan aparat penegak hukum tidak berubah menjadi alat kesewenang-wenangan.
Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, kewenangan praperadilan mengalami perluasan signifikan, mencakup pula uji keabsahan penetapan tersangka. Artinya, praperadilan kini bukan lagi sekadar “pengadilan kecil” yang memeriksa formalitas prosedur, melainkan forum yudisial awal yang menjamin tegaknya prinsip due process of law.
Dalam praktiknya, praperadilan telah memberi dampak substantif bagi perlindungan hak individu. Sejumlah putusan penting membatalkan penetapan tersangka yang cacat prosedur, sekaligus menegaskan bahwa aparat hukum tidak kebal dari mekanisme kontrol. Namun, efektivitas forum ini masih jauh dari ideal.
Beberapa tantangan utama yang mengemuka antara lain:
1. Inkonsistensi putusan antar pengadilan, yang melemahkan kepastian hukum.
2. Keterbatasan waktu persidangan (7 hari), sehingga hakim sering kesulitan menggali fakta hukum secara mendalam.
3. Minimnya akses pemohon terhadap dokumen penyidikan, yang membuat posisi tersangka tidak seimbang dengan aparat.
4. Potensi penyalahgunaan praperadilan oleh tersangka elit, yang menjadikannya sebagai tameng untuk menghindari proses pidana.
Kondisi ini menegaskan bahwa praperadilan membutuhkan reformasi sistemik. Beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan meliputi:
Revisi KUHAP agar kewenangan praperadilan yang diperluas oleh MK memiliki legitimasi eksplisit.
Pelatihan khusus bagi hakim agar lebih peka terhadap prinsip due process dan hak asasi manusia.
Digitalisasi sistem peradilan, mulai dari pendaftaran daring hingga publikasi putusan terbuka, guna meningkatkan transparansi.
Penguatan pengawasan publik dan peran masyarakat sipil, agar praperadilan tidak hanya menjadi arena formalitas, melainkan forum substantif untuk keadilan.
Dalam konteks negara hukum demokratis, praperadilan bukan sekadar instrumen teknis, melainkan pilar substantif dalam menjaga keadilan, membatasi kesewenang-wenangan negara, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dengan kata lain, menguatkan praperadilan berarti menegaskan komitmen negara untuk menjunjung tinggi martabat dan kebebasan warganya.
Referensi :
1. Asikin, Z. (2023). Keadilan prosedural dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penerbit Hukum Progresif.
2. Asshiddiqie, J. (2019). Konstitusi dan hak asasi manusia.Asshiddiqie, J. (2021). Hukum acara pidana dan perlindungan konstitusional tersangka.
3. Azhar, H. (2020). Catatan kritis atas praperadilan: Antara harapan dan formalitas.Barendt, E. (2010). An introduction to constitutional law. Oxford University Press.Budiman, A. (2023). Perlindungan hak tersangka melalui praperadilan. Genta Publishing.
Arthur Noija SH